MENDOBRAK ARTIKULASI SWASEMBADA PANGAN/ BERAS :
Sebuah Tinjuan Kritis untuk Mimpi Bulog 2020
Oleh :
M.A. Khomsin,S.Pd.I.
Desa Glagahwaru adalah sebuah desa yang terletak di Tenggara Kota Kudus, dimana mayoritas penduduknya adalah petani. Beraneka ragam tanaman dapat dihasilkan, mulai dari padi, ketela, jagung, kacang hijau sampai bawang merah dan tomat. Setiap petani bisa menjual sampai dengan + ¾ hasil panen kepada tengkulak, dengan sisanya digunakan sebagai persediaan sampai tiba panen berikut atau hanya sekedar dibagikan kepada tetangga dan kerabat. Dari kenyataan di atas, apakah Desa Glagahwaru sudah bisa dikatakan swasembada pangan?, meskipun di sisi lain, masyarakat masih membeli keripik tela, tepung beras, sereal, gula jagung dan lainnya dengan harga relatif tinggi. Secara sederhana, dapat digambarkan, satu sisi masyarakat Glagahwaru menjual bahan baku (hasil panen), namun di sisi lain, mereka membeli produk yang terbuat dari bahan baku asli dari mereka dengan harga yang tinggi bila di bandingkan dengan harga jual hasil panen mereka. Dan, kenapa mereka tidak berpikir untuk memproduksinya sendiri?.
Dalam kaitan itu, apakah Indonesia sudah bisa dikatakan swasembada pangan/ swasembada beras? menanggapi resistensi beberapa daerah atas impor beras, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, meski sudah swasembada beras, Indonesia tetap perlu mengimpor beras untuk menjamin stok dalam negeri, menstabilkan harga, dan politik perdagangan internasional (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0609/04/utama/ 2926936.htm). Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan optimismenya program realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog tahun anggaran 2009, bisa tercapai kembali seperti di tahun 2008, dengan demikian, pemerintah bisa melanjutkan program swasembada beras yang dicapai pada tahun 2008 itu, lalu pemerintah menetapkan keberhasilan swasembada beras dan tidak memutuskan impor beras (http://hariansib.com/2009/04/07/bulog-catat-laba-rp101-miliar/). Namun, hemat penulis, Indonesia belum bisa dikatakan swasembada beras, hanya karena berhasil mencapai target pengadaan beras.
Di era orde baru, Indonesia pernah mengklaim telah swasembada pangan, meskipun dibagian kehidupan lain, masih ada masyarakat yang kesulitan makan, gizi buruk, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Hal ini terjadi, karena pemerintah sangat terobsesi akan prestasi-prestasi dan pengakuan demi pengakuan. Agar momentum ‘kelaparan di lumbung padi’ pada era orde baru tidak ‘berulang’ (sengaja diulang kembali) di Era Reformasi ini, maka term swasembada pangan harus direvisi artikulasinya - kalau masih kurang harus direnovasi artikulasinya - sehingga swasembada pangan diartikan sebagai kondisi yang menggambarkan kesejahteraan pangan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya.[1]
Jika indikator swasembada pangan di Orde Baru adalah ekspor beras, maka di Era Reformasi ini, indikator swasembada beras/ pangan harus dikembangkan menjadi :
1. Kecukupan kebutuhan beras/ pangan dalam negeri, sehingga tidak ada kasus kelaparan, kesulitan mendapatkan pangan/ beras, gizi buruk di daerah terpencil, termasuk siapnya beberapa program untuk mengatasi gagal panen, musibah/ bencana.
2. Sirkulasi beras/ pangan dalam setiap transaksinya, harus selalu menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat :
a. Petani sebagai produsen;
b. Pembeli padi (tengkulak);
c. Pemroses padi menjadi beras (bakul);
d. Pengusaha beras, dan yang paling penting
e. Pembeli/ pemakai (konsumen).
Adapun pemerintah, adalah sebagai penanggungjawab atas peredaran bahan pangan/ beras. Dan, keberhasilan dalam menunaikan tanggung jawabnya itu adalah, keuntungan pemerintah dalam setiap bargainingnya, baik secara ekonomi, politik, maupun dalam konteks perdagangan internasional. "Menurut saya Bulog dikembalikan seperti semula sebagai penyangga bukan untuk mencari keuntungan" Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Ahmad Anshori Mattjik (http://beritasore.com/2008/12/22/kkn-di-perum-bulog-merajalela/).
3. Bilamana kedua indikator di atas sudah terpenuhi, ekspor dapat dilaksanakan. Tetapi, ekspor tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan untuk memosisikan Indonesia dalam otoritasnya sebagai penyedia bahan pangan dunia (dalam ragam olahan dari hasil bumi Indonesia).
Dengan indikator swasembada pangan di atas, penulis berani menjamin, akan ada pengakuan dari dunia internasional terhadap swasembada pangan Indonesia. Dan itulah sebenarnya mimpi Bulog 2020. Kita harus banyak terinspirasi, kenapa banyak negara ‘bertekuk lutut’ kepada Negara-Negara Timur Tengah hanya karena minyaknya? Jawabannya adalah, karena kebutuhan akan energi (minyak). Tapi, kenapa kita lantas mempertanyakan kepastian kebutuhan dunia terhadap bahan pangan? Apakah seseorang bisa hidup tanpa makan?.
Indonesia punya potensi, tapi sering menjadi korban prestasi dan obsesi para pelaku kebijakan. Sebagai negara agraris, Indonesia terus tergerus, bagaimana tidak? luas daratan Indonesia yang hanya sepertiga luas wilayah Indonesia, terus direduksi hutan lindung, hutan produksi, permukiman, industri, dan kebutuhan infrastruktur yang jumlahnya terus meningkat, disamping adanya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dengan laju yang bisa mencapai 80.000 hektar per tahun serta diimbangi dengan kemampuan cetak sawah nasional maksimal, masih di bawah laju alih fungsinya.
Dengan tekad untuk swasembada pangan 2020, pelaksana kebijakan terlebih Bulog, harus benar-benar membuat gebrakan besar. Mulai dari merelokasi tempat-tempat tidak produktif untuk pertanian sampai dengan pengamanan kebijakan penetapan harga gabah, harga beras serta sirkulasi bahan pangan nasional. Dengan kondisi yang benar-benar swasembada pangan sebagaimana dimaksudkan, berarti sudah ada perhatian khusus terhadap berbagai kelompok vertikal (multi strata; petani, nelayan, buruh, sektor informal, masyarakat adat). Menetapkan substansi konstitusi baru yang lebih “populis” itu akan membuka peluang kita dapat menghasilkan “bangunan sosial” yang lebih adil dan tangguh. Tidak terbahasnya “ke-bhineka-an” Indonesia, terutama aspek vertikalnya dalam konstitusi mengakibatkan terlupakannya dan tertinggalnya massa “poros bawah” yang merupakan kelompok mayoritas.
Untuk memulai swasembada pangan berdasar artikulasi baru pada tahun 2020, kita perlu tancap gas, serukan revolusi pertanian Indonesia. Karena, disadari atau tidak, misi ini bisa dikatakan mission impossible. Kita lihat profil lahan pertanian di Brasil. Luas lahan pertanian Indonesia keseluruhan yang sekitar 21 juta hektar itu hanya sama dengan luas lahan kedelai yang ada di Brasil yang penduduknya lebih kecil dari Indonesia (mendekati 200 juta), luas sawah Indonesia sama dengan luas lahan tebu di Brasil, sementara luas ladang penggembalaan sapi di Brasil (220 juta hektar) lebih luas dari seluruh daratan di Indonesia (190 juta hektar). (Anton Apriyantono, Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu, http://www.kompas.com/kompascetak/read.php? cnt=.xml.2008.04.09.01170223). Tetapi, masalah kita sekarang adalah, bagaimana dapat mempengaruhi proses politik yang menentukan dalam mengarahkan pembangunan pertanian dalam arti luas, mencakup usaha perikanan laut dan pengolahan sumberdaya hutan, sekaligus mendukung pembangunan pedesaan yang saling dukung dan berkelanjutan ?.
Ann Booth (1988) bahwa di antara negara-negara pengekspor minyak hanya Indonesia yang waktu itu (awal 1970-an) tak lupa melakukan investasi dalam pembangunan pertanian, termasuk membangun industri pupuk kimia. Peningkatan dalam produksi beras (kg/kapita) pantas disebut “revolusi” karena tercapai dalam masa relatif singkat, yaitu belasan tahun. Geertz, sebagai pencetus ide “evolusi pertanian” mengaitkan suatu perbaikan kondisi pertanian di Indonesia pada suatu syarat pokok, yaitu perubahan yang penting dalam visi para pemuka bangsa, dalam memilih corak pembangunan yang memberi harapan lebih. Jika merujuk ke sumbangan pemikiran Kasryno, dalam hal petani pangan khususnya (Widyakaraya Pangan/Gizi, 2000), isinya tak lain adalah suatu visi baru dalam pembanguan pertanian kita. Ada pula sumbangan pemikiran lainnya, Ketua PERHEPI, Dirjen Bina Perkebunan berpeluang mengembangkan visi mengenai masa depan subsistem agribisnis Indonesia, terutama petani-kebun, penghasil bahan mentah industri yang diekspor. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/ artikel_5.htm.).
Beranjak dari narasi di atas, diharapkan, para pelaku kebijakan tidak asal mengklaim swasembada pangan/ beras, apalagi jika swasembada pangan itu hanya diorientasikan dan dipresentasikan secara politis. Sesungguhnya, swasembada pangan benar-benar merupakan kondisi yang menggambarkan kesejahteraan pangan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Dan swasembada pangan atau tidak, masyarakat sendirilah yang merasakannya. Kalaupun mau ekspor beras/ bahan pangan, janganlah ada klaim swasembada beras/ pangan, tapi bermimpilah untuk otoritas Indonesia sebagai penyedia bahan pangan dunia.
[1] Lihat juga Surplus Beras vs Swasembada Beras, Dr. Ir. Sapuan Gafar Pengamat Perberasan, http://nasih.staff.ugm.ac.id/a/pert/20061006%20sur.htm,, 06 October 2006.


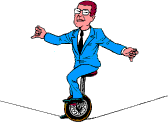
0 komentar:
Posting Komentar